Written by Nadya Fitaloka
Saat ini, dunia tengah dihadapi oleh berbagai macam tantangan kelestarian lingkungan, mulai dari pengurangan produksi emisi karbon, peningkatan frekuensi bencana akibat perubahan iklim, hingga kerusakan ekosistem yang mengancam keanekaragaman hayati. Tantangan ini telah menjadi concern utama bagi setiap negara di dunia dan membutuhkan mitigasi yang cepat untuk menanggulangi fenomena ini. Berbagai macam aktivitas manusia telah mendorong terjadinya kerusakan lingkungan dengan cepat. Ekosistem serta lingkungan hidup bumi, pelan-pelan merusak akibat limbah yang dihasilkan dari kegiatan manusia. Selain limbah plastik yang menjadi salah satu perhatian dunia, limbah industri tekstil juga menjadi pusat perhatian yang sama. Limbah industri tekstil atau limbah tekstil telah meresahkan dunia karena sifatnya yang sulit terurai dan jumlahnya yang terus meningkat. Dalam dunia yang telah modern ini, banyak sekali perusahaan dalam bidang tekstil yang terus menerus memproduksi pakaian massal dalam waktu yang singkat. Fenomena ini kerap disebut sebagai fast fashion.
Tren fast fashion telah mengguncang industri pakaian global. Fast fashion sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan industri tekstil yang memproduksi pakaian secara cepat dalam harga yang relatif murah. Industri fashion telah muncul sejak abad ke-18 saat revolusi industri inggris berlangsung. Revolusi ini memperkenalkan kemudahan dalam memproduksi sesuatu seperti pakaian. Sejak saat itu, masyarakat dapat dengan mudah memproduksi, membeli, dan menggunakan pakaian yang telah diperjual belikan. Hingga saat ini, fashion telah menjadi suatu barang primer yang dapat diperoleh dengan sangat mudah. Di awal tahun 1900-an, pakaian hanya diproduksi setiap 4 musim, yaitu musim semi gugur, panas, dan dingin. Memasuki tahun 1975, merk ternama produser pakaian, Zara, muncul ke publik dengan menawarkan model pakaian yang modern dan stylish.. Perusahaan ini mulai menggunakan konsep fast fashion yang memproduksi model pakaian baru setiap minggu dan meninggalkan konsep slow fashion yang hanya memproduksi setiap musim berganti. Sejak saat itu, mulai banyak terlahir produsen pakaian yang menggunakan konsep fast fashion.
Fast fashion memiliki karakteristik yang sama setiap masa produksinya, mulai dari penggunaan bahan baku yang memiliki jangka pakai yang pendek, harga yang ditawarkan sangat terjangkau, memiliki model yang sama, dan jumlah koleksi yang sangat melebihi kebutuhan manusia. Pakaian yang diproduksi seringkali didasarkan pada gaya busana yang digunakan oleh selebritas dalam peragaan busana “fashion week”. Tren gaya busana ini bergerak dengan sangat cepat sehingga para konsumen akan dengan cepat mengganti koleksi busana mereka. Hal ini diperparah dengan fenomena Fear Of Missing Out (FOMO) yang bermakna ketakutan akan ketertinggalan suatu tren tertentu yang sedang terkenal sehingga sifat konsumtif para konsumen akan merasa ketertinggalan jika mereka tidak ikut mengoleksi pakaian keluaran baru pada musim tertentu. Yang terjadi setelah konsumen secara terus menerus konsumtif akan tren pakaian terbaru busana lama mereka yang sudah tidak mereka pakai akan terbuang dan berakhir di tempat pembuangan akhir, yang akan terus menumpuk sehingga menciptakan dampak lingkungan yang mengganggu. Menurut laporan UNEP 2023, terdapat 92 juta ton limbah tekstil yang dihasilkan setiap tahunnya. Angka ini tentunya bukan angka yang kecil untuk hitungan satu tahun.
Dalam kegiatan memproduksi pakaian, fashion industry membutuhkan 79 trilliun liter air per tahunnya dan sebanyak 2.700liter air hanya untuk memproduksi satu kaos katun (Bailey et al., 2022). Hal ini untuk memenuhi proses penanaman kapas, produksi, pewarnaan, hingga finishing produk. Jumlah air yang sangat besar ini menempatkan tekanan pada sumber daya air di berbagai negara, terutama di wilayah yang sudah mengalami kekeringan. Misalnya, penanaman kapas intensif di India dan Uzbekistan telah menyebabkan penurunan kualitas tanah dan berkurangnya ketersediaan air bersih. Tercatat pada penelitian yang dilakukan oleh Albab et al., 2024 industri fast fashion menyumbang sekitar 20% dari total limbah air di dunia sehingga berkontribusi pada penurunan kualitas air bersih secara global. Tak hanya itu, pakaian yang menggunakan bahan baku plastik seperti bahan polyester membutuhkan ratusan tahun untuk terurai. Proses pembusukan inilah yang menghasilkan emisi gas rumah kaca yang selanjutnya berkontribusi terhadap pemanasan global dan merusak lapisan ozon bumi (Ramadhan, 2024). Kadang kala, para perusahaan yang bergerak dalam industri ini, memusnahkan barang-barang mereka yang tidak terjual atau tak layak jual dengan membakarnya dan melepaskan karbon dioksida ke lingkungan bebas. Hal ini sangat merusak lingkungan dan dapat meningkatkan volume emisi karbon di dunia dan diprediksi limbah tekstil akan menyumbang sebesar 20% emisi karbon pada tahun 2050 dan telah menjadi sumber polutan terbesar kedua di bumi setelah minyak (Albab et al.,2024).
Di Indonesia, Sungai Ciliwung menjadi contoh nyata akan bahayanya limbah tekstil yang menumpuk. Pada tahun 2018 Sungai Ciliwung menjadi sungai yang paling tercemar di dunia, berbagai limbah mencemari sungai ciliwung dan merusak keseimbangan ekosistem di kawasan itu. Limbah yang paling mendominasi mencemari sungai tersebut yaitu limbah tekstil. Limbah ini berasal negara penghasil seperti China dan Thailand. Awalnya, negara penghasil mengekspor pakaian “terbuang” ini untuk diberikan kepada perusahaan yang menerima pemusnahan massal barang tak layak pakai. Namun, setelah sampai, alih alih memusnahkan barang tersebut perusahaan tersebut malah menyortir kembali pakaian yang tak layak itu untuk dijual per-bal untuk meraup keuntungan yang lebih banyak. Dari total 100% barang pakaian impor, hanya 20-30% yang masih bisa dijual lagi ke konsumen. Sisa 70% sampah pakaian akan dimusnahkan dengan pembakaran massal yang menghasilkan 2 kali lipat emisi karbon dibanding saat produksi pakaian tersebut. Pakaian yang tidak laku setelah sampai ke tangan penjual di Indonesia, berakhir menumpuk di tempat pembuangan sampah dan tempat tak layak seperti Sungai Ciliwung.
Tak hanya berdampak buruk dalam aspek lingkungan, industri fast fashion pun berdampak buruk dalam bidang sosial dan etis. Karena produksi yang dilakukan secara besar dengan harga yang murah, perusahaan fashion membuka pabrik produksi mereka di negara berkembang untuk mengambil keuntungan dari biaya tenaga kerja yang lebih murah. Para pekerja biasanya didominasi oleh ibu-ibu pekerja yang membutuhkan penghasilan tambahan untuk keluarganya. Namun, ditemukan juga pekerja anak dibawah umur, para pekerja ini dieksploitasi bekerja selama 16 jam perhari dengan upah yang tidak layak. Hal ini dilakukan karena banyaknya permintaan dari konsumen sehingga mengharuskan mereka memproduksi busana dengan cepat dalam kuantitas besar. Dilansir dari International Law and Policy Brief, dari total 75 juta pabrik fashion di dunia, kurang dari 2% diantaranya memiliki upah yang layak. Fakta ini memperlihatkan bagaimana kegiatan produksi yang dilakukan para perusahaan yang menganut industri fast fashion sangat merugikan dan melanggar HAM para pekerja buruh.
Bangladesh menjadi negara terdampak eksploitasi pekerja buruh garmen (Gunawan et al., 2023). Salah satu pekerja dengan upah paling rendah di dunia berasal dari pekerja Bangladesh. Korban eksploitasi tidak hanya wanita dewasa tetapi juga anak-anak. Anak-anak yang seharusnya pergi ke sekolah dan belajar justru terpaksa bekerja di pabrik pakaian untuk membantu perekonomian keluarga. Bahkan wanita hamil sering menolak mengambil cuti untuk memperoleh uang untuk kebutuhan persalinan mereka (Apsari et al., 2022). Kadang-kadang, peralatan yang digunakan di pabrik dapat membahayakan keselamatan pekerja, terutama anak-anak. Selain itu, ada banyak bagian lain dari ketidakadilan dan penindasan yang dialami pekerja garmen Bangladesh. Sampai akhirnya, pada pertengahan tahun 2013, para pekerja di Bangladesh menggelar protes untuk industri garmen yang memberi upah tak layak. Para pekerja marah atas usulan pemerintah menaikan upah minimum yang dianggap terlalu rendah karena hanya menaikan upah dari sekitar US$38 menjadi US$66 per bulan. Protes ini merupakan puncak dari ketidakpuasan yang sudah lama terpendam, terutama setelah tragedi Rana Plaza yang terjadi pada April 2013, ketika sebuah bangunan pabrik di pinggiran kota Dhaka roboh dan menewaskan lebih dari 1.100 pekerja. Ini memicu kecaman di seluruh dunia dan menunjukkan kondisi kerja yang buruk dan kurangnya perlindungan bagi pekerja garmen Bangladesh.
Dampak negatif yang telah mempengaruhi berbagai aspek ini tentunya memaksa industri fast fashion untuk melakukan upaya dan kebijakan untuk menanggulangi dampak negatifnya. Salah satu langkah utama yang diambil oleh pelaku industri adalah memperkenalkan inisiatif keberlanjutan dalam rantai produksi. Banyak perusahaan mulai mengadopsi penggunaan bahan baku yang lebih ramah lingkungan, seperti serat organik, kapas daur ulang, dan poliester hasil daur ulang. Penggunaan bahan-bahan ini diharapkan dapat menekan konsumsi sumber daya alam dan mengurangi limbah tekstil yang sulit terurai (Niinimäki et al., 2020). Selain itu, program pengumpulan pakaian bekas juga mulai diterapkan di berbagai negara. Konsumen didorong untuk mengembalikan pakaian yang sudah tidak terpakai ke toko-toko tertentu agar dapat didaur ulang atau diproses kembali menjadi produk baru. Upaya ini tidak hanya bertujuan mengurangi limbah tekstil, tetapi juga memperpanjang siklus hidup pakaian sehingga mengurangi kebutuhan produksi baru yang berlebihan. Beberapa perusahaan juga mulai berinvestasi dalam teknologi pewarnaan yang lebih hemat air dan ramah lingkungan untuk mengurangi pencemaran air yang diakibatkan oleh proses produksi tekstil.
Dari sisi regulasi, pemerintah di berbagai negara telah memberlakukan kebijakan yang lebih ketat terkait pengelolaan limbah tekstil dan perlindungan hak pekerja. Uni Eropa, misalnya, mulai menerapkan prinsip extended producer responsibility (EPR) yang mewajibkan produsen bertanggung jawab atas limbah produk mereka hingga ke tahap akhir siklus hidup. Kebijakan ini mendorong produsen untuk merancang produk yang lebih mudah didaur ulang dan mengurangi limbah yang berakhir di tempat pembuangan akhir (European Commission, 2023). Selain itu, beberapa negara telah memperkuat perlindungan tenaga kerja melalui regulasi yang mewajibkan upah layak, jam kerja manusiawi, dan standar keselamatan kerja di pabrik-pabrik tekstil (House of Commons Environmental Audit Committee, 2019). Kesadaran konsumen juga menjadi faktor penting dalam mendorong perubahan perilaku industri. Gerakan slow fashion berkembang sebagai respons terhadap pola konsumsi fast fashion yang boros dan tidak berkelanjutan. Slow fashion menekankan kualitas, ketahanan, dan etika produksi, serta mendorong konsumen untuk membeli lebih sedikit, memilih produk yang tahan lama, dan mendukung produsen yang bertanggung jawab (Bick et al., 2018). Kampanye edukasi publik yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah dan komunitas lingkungan turut memperkuat perubahan pola konsumsi ini, memperkenalkan konsep seperti “buy less, choose well, make it last” sebagai gaya hidup baru yang lebih berkelanjutan.
Perkembangan teknologi telah membuka peluang besar dalam upaya penanggulangan dampak fast fashion. Inovasi seperti teknologi pewarnaan digital yang hemat air dan energi, serta penggunaan enzim dalam proses pencucian kain, mampu mengurangi konsumsi bahan kimia berbahaya dan limbah cair yang dihasilkan industri tekstil (Zamani et al., 2017). Industri tekstil juga mulai mengadopsi model bisnis ekonomi sirkular, di mana limbah produksi diolah kembali menjadi bahan baku untuk produk baru. Konsep circular fashion ini tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru melalui inovasi desain dan pengembangan produk yang dapat didaur ulang. Beberapa perusahaan telah meluncurkan lini produk yang seluruhnya terbuat dari bahan daur ulang, serta menyediakan layanan reparasi dan perawatan pakaian untuk memperpanjang umur pakai produk. Di tingkat global, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan organisasi internasional semakin diperkuat untuk mengatasi tantangan lintas batas yang ditimbulkan oleh industri fast fashion. Forum-forum internasional seperti United Nations Alliance for Sustainable Fashion dan Sustainable Apparel Coalition menjadi wadah bagi pertukaran pengetahuan, pengembangan standar keberlanjutan, dan advokasi kebijakan yang lebih progresif (United Nations Alliance for Sustainable Fashion, 2020). Negara-negara produsen tekstil juga didorong untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan limbah dan memperkuat hak-hak pekerja melalui bantuan teknis dan investasi dalam infrastruktur hijau (Student Briefs, 2021).
Fast fashion telah menjadi bagian dari kehidupan modern, namun kehadirannya membawa konsekuensi serius bagi lingkungan dan masyarakat. Dalam upaya mengejar tren dan memenuhi kebutuhan pasar yang cepat berubah, industri ini menciptakan siklus produksi yang masif dan tidak berkelanjutan. Mulai dari penggunaan air yang berlebihan, pencemaran limbah kimia, hingga emisi karbon yang tinggi, industri fast fashion telah memberi tekanan besar terhadap ekosistem global. Tidak hanya berdampak pada lingkungan, fast fashion juga menyimpan sisi gelap dalam aspek sosial. Eksploitasi buruh, terutama perempuan dan anak-anak di negara berkembang, menjadi realita yang masih sering diabaikan oleh konsumen dunia. Kasus di Bangladesh memperlihatkan bagaimana industri ini mengejar keuntungan dengan mengorbankan keselamatan dan kesejahteraan para pekerjanya. Rendahnya upah, kondisi kerja yang tidak layak, hingga minimnya perlindungan hukum menjadi gambaran jelas ketimpangan yang terjadi di balik pakaian murah yang mudah didapat. Tragedi Rana Plaza pada 2013 adalah pengingat bagaimana industri ini tega mempertaruhkan nyawa seseorang demi untuk memenuhi permintaan konsumen yang begitu massal. Namun, di tengah krisis ini, benih perubahan mulai tumbuh. Perusahaan fashion mulai beralih ke bahan ramah lingkungan dan teknologi produksi yang lebih hemat air. Pemerintah di beberapa negara juga menerapkan regulasi yang menuntut tanggung jawab produsen atas limbah yang dihasilkan. Di sisi lain, kesadaran konsumen mulai berubah. Gerakan slow fashion hadir sebagai alternatif yang menekankan pada kualitas, ketahanan, dan etika produksi. Kehadiran fast fashion tidak bisa ditinggalkan dengan mudah, namun dapat dikendalikan dengan langkah-langkah bijak dan kolaborasi dari semua pihak. Jika kita sebagai para konsumen mampu membatasi perilaku konsumerisme terhadap busana yang kita pakai, maka masa depan industri fashion dapat menjadi lebih etis dan ramah lingkungan.
References
Albab, W. U., Mardiah, A. R., Ranjani, G., Karina, G. D., & Safitri, M. N. (2024). Pengaruh industri fast fashion terhadap pencemaran lingkungan dan penurunan keadilan antar generasi. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), 5(3), 94–103. https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i3.22830
Apsari, R. D., Yuniati, S., & Indriastuti, S. (2022). Penerapan Konvensi ILO pada industri garmen Bangladesh (Studi kasus: Diskriminasi pekerja garmen perempuan). Electronical Journal of Social and Political Sciences, 9(3), 168–172. https://doi.org/10.33510/ejsp.v9i3.2022
Bailey, K., Basu, A., & Sharma, S. (2022). The environmental impacts of fast fashion on water quality: a systematic review. Water, 14(7), 1073. . https://doi.org/10.3390/w14071073
Bick, R., Halsey, E., & Ekenga, C. C. (2018). The global environmental injustice of fast fashion. Environmental Health, 17(92). https://doi.org/10.1186/s12940-018-0433-7
European Commission. (n.d.). EU Strategy for sustainable and circular textiles. European Commission. Retrieved July 18, 2025, from https://environment.ec.europa.eu/strategy/textiles-strategy_en
Gunawan, Y., Matahariza, A., & Putri, W. K. (2023). The dark side of fast fashion: Examining the exploitation of garment workers in Bangladesh. Jurnal Hukum dan Peradilan, 12(3), 441–468. https://doi.org/10.25216/jhp.12.3.2023.441-468
House of Commons Environmental Audit Committee (2019). Fixing Fashion: Clothing Consumption and Sustainability.
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmenvaud/1952/1952.pdf
Niinimäki, K., Peters, G., Dahlbo, H., Perry, P., Rissanen, T., & Gwilt, A. (2020). The environmental price of fast fashion. Nature Reviews Earth & Environment, 1(4), 189-200. https://doi.org/10.1038/s43017-020-0039-9
Rahman, T. (2021). What’s happening in Bangladesh’s garment industry? Economics Observatory. https://www.economicsobservatory.com/whats-happening-in-bangladeshs-garment-industry
Ramadhan, A. F. (2024). Tren fast fashion pakaian masa new normal di Indonesia: Efektivitas konsep sustainable fashion terhadap lingkungan. Journal of Waste and Sustainable Consumption, 1(2), 77–89. https://doi.org/10.61511/jwsc.v1i2.2024.1247
Ross, E. (2021). Fast fashion getting faster: A look at the unethical labor practices sustaining a growing industry. International Law & Policy Brief (ILPB). George Washington University Law School. https://studentbriefs.law.gwu.edu/ilpb/2021/10/28/fast-fashion-getting-faster-a-look-at-the-unethical-labor-practices-sustaining-a-growing-industry/
UNEP. (2023). Sustainability and circularity in the textile value chain: A global roadmap [Full report]. United Nations Environment Programme. https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/2023-12/Full%20Report%20-%20UNEP%20Sustainability%20and%20Circularity%20in%20the%20Textile%20Value%20Chain%20A%20Global%20Roadmap_0.pdf
Zamani, B., Sandin, G., & Peters, G. M. (2017). Life cycle assessment of clothing libraries: can collaborative consumption reduce the environmental impact of fast fashion?. Journal of cleaner production, 162, 1368-1375. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.06.128






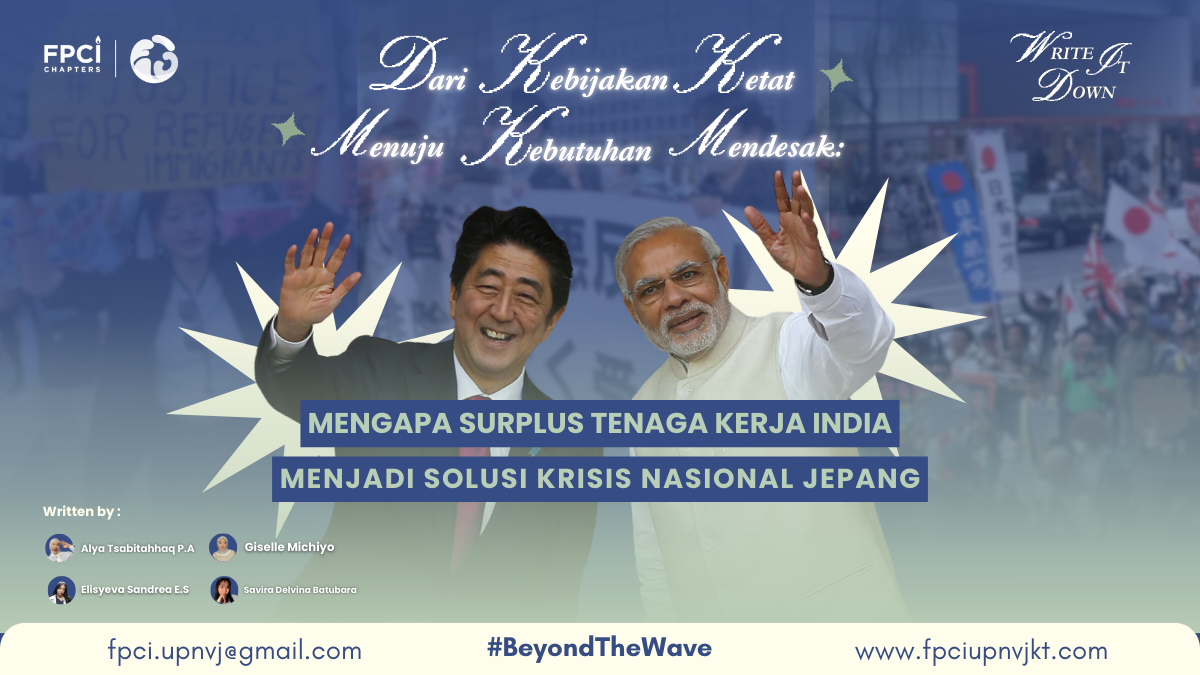

Tinggalkan Balasan