Ditulis oleh Freesia Aryunia
Eurovision Song Contest adalah kompetisi musik tahunan internasional yang disiarkan secara langsung dan diikuti oleh negara-negara anggota European Broadcasting Union (EBU). Setiap negara peserta mengirimkan satu lagu orisinal untuk ditampilkan di panggung internasional, kemudian dilakukan pemungutan suara oleh juri profesional dan penonton untuk menentukan pemenangnya. Ajang ini bukan sekadar kontes musik, melainkan telah berkembang menjadi fenomena budaya global yang merepresentasikan keberagaman identitas, politik, dan diplomasi budaya Eropa.
Eurovision pertama kali digelar pada tahun 1956 di Lugano, Swiss, dengan tujuh negara peserta. EBU merancang kompetisi ini sebagai upaya memperkuat kohesi sosial-politik di Eropa pasca-Perang Dunia II, sekaligus menguji teknologi siaran televisi transnasional. Sistem kompetisi berbasis voting yang dipilih sejak awal dimaksudkan untuk mendorong solidaritas antarnegara serta memperkuat rasa kebersamaan melalui musik dan budaya populer.
Dalam perkembangannya, Eurovision menjadi salah satu acara televisi terbesar di dunia, dengan jangkauan audiens global mencapai 166 juta penonton pada edisi 2025 dan partisipasi lebih dari 37 negara, termasuk non-Eropa seperti Israel dan Australia. Besarnya jumlah audiens menjadikan Eurovision bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi budaya dan simbol soft power transnasional.
Meskipun didefinisikan sebagai hiburan non-politis, kontes ini tidak pernah benar-benar lepas dari dinamika politik. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya pola voting yang dipengaruhi aliansi geopolitik maupun kedekatan budaya regional, serta seringkali mencerminkan isu politik kontemporer. Hal ini membuat Eurovision menjadi wadah di mana seni, budaya, dan politik internasional saling berkesinambungan.
European Broadcasting Union (EBU), penyelenggara Eurovision, secara eksplisit menetapkan dalam aturan bahwa kontes lagu ini harus bebas dari konten politik. Salah satu ketentuan inti terdapat dalam Rules of the 54th Eurovision Song Contest (2009), Section 4 Rule 9, yang berbunyi: “The lyrics and/or performance of the songs shall not bring the Shows or the Eurovision Song Contest as such into disrepute. No lyrics, speeches, gestures of a political or similar nature shall be permitted … A breach of this rule may result in disqualification.” Aturan ini mencerminkan komitmen formal EBU untuk menjaga Eurovision sebagai kontes hiburan yang non-politik dan universal, terlepas dari latar belakang politik para peserta.
Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa kasus yang memperlihatkan bahwa pelaksanaan aturan ini tidak selalu sederhana dan konsisten. Salah satu contoh paling awal adalah kasus Georgia pada tahun 2009. Lagu hasil seleksi Georgia berjudul “We Don’t Wanna Put In” diajukan tetapi kemudian ditolak oleh EBU karena dianggap mengandung permainan kata yang merujuk kepada Perdana Menteri Rusia, Vladimir Putin (“Put In”). EBU menilai lirik lagu tersebut melanggar Rule 9 mengenai larangan konten politik. Georgia kemudian ditawari untuk mengubah lirik atau memilih lagu alternatif, namun tidak melakukannya, sehingga akhirnya menarik diri dari kontes tersebut.
Kasus yang lebih kontemporer dan kompleks muncul pada Eurovision 2021 dengan Belarus. Grup Galasy ZMesta diajukan oleh penyiar nasional Belarus (BTRC) dengan lagu Ya Nauchu Tebya (“I’ll Teach You”), yang segera mendapat kecaman bahwa liriknya mengejek aksi protes terhadap rezim Aleksandr Lukashenko. Lirik seperti “I will teach you to toe the line / You will be happy and glad about everything” dianggap memiliki nuansa politik yang sangat jelas, bukan sekadar satire ringan. EBU kemudian menyatakan bahwa lagu tersebut “puts the non-political nature of the contest in question”, dan meminta Belarus untuk mengubah entri tersebut atau memilih lagu lain. Ketika pengajuan alternatif (lagu baru oleh grup yang sama) juga ditolak karena masih dianggap melanggar aturan, Belarus akhirnya diskualifikasi dari Eurovision 2021.
Salah satu yang paling menarik dari Eurovision adalah pola pemberian suara antarnegara. Sejak awal tahun 2000-an, sejumlah analisis kuantitatif menunjukkan bahwa hasil kontes tidak sepenuhnya ditentukan oleh kualitas musik atau penampilan, melainkan juga oleh faktor politik, geografis, dan sosial. Fenomena ini dikenal sebagai bloc voting, yakni kecenderungan negara-negara yang memiliki kedekatan tertentu untuk saling memberikan poin tinggi. Penelitian empiris berbasis model ekonometrik dan analisis jaringan sosial menegaskan bahwa ada konsistensi pola dukungan di kawasan tertentu seperti Skandinavia, Balkan, dan negara-negara runtuhan Uni Soviet. Hal ini berarti Eurovision tidak hanya menjadi ajang kompetisi musik, tetapi juga laboratorium sosial yang merefleksikan solidaritas maupun ketegangan geopolitik di Eropa.
Spierdijk dan Vellekoop (2009), misalnya, menggunakan data panel dari berbagai edisi Eurovision dan menemukan adanya keteraturan statistik dalam alokasi poin. Negara-negara cenderung memberikan skor lebih tinggi kepada tetangga geografis atau negara dengan ikatan budaya kuat, bahkan setelah dikontrol dengan kualitas lagu melalui hasil penjurian independen. Ginsburgh dan Noury (2008) juga mengonfirmasi bahwa preferensi voting lebih banyak dipengaruhi oleh kedekatan politik, linguistik, serta hubungan ekonomi dibandingkan dengan aspek artistik. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa Eurovision bukan sekadar arena estetika musik, tetapi juga cerminan jaringan kekuasaan dan pertalian sosial di antara negara-negara Eropa.
Selain faktor kedekatan geografis dan budaya, diaspora menjadi variabel penting yang menjelaskan arah pemberian suara. Negara-negara dengan populasi migran yang besar di luar negeri cenderung menerima skor lebih tinggi dari negara tujuan migrasi mereka. Charron (2013) menekankan bahwa ukuran komunitas diaspora dapat memengaruhi intensitas televoting, terutama setelah sistem pemungutan suara memberi bobot signifikan kepada publik melalui telepon dan SMS. Hal ini menjelaskan mengapa negara-negara seperti Armenia, Turki, dan Polandia sering kali mendapatkan dukungan konsisten dari negara-negara dengan komunitas diaspora yang besar, terlepas dari kualitas musikal entri mereka. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana migrasi internasional membentuk politik budaya transnasional, dengan Eurovision menjadi salah satu arena di mana identitas diaspora diekspresikan secara simbolis.
Pola geopolitik dalam voting juga semakin jelas ketika sistem pemungutan suara menghadapi anomali yang mencurigakan. Pada kontes 2022, EBU menemukan indikasi kolusi di antara enam negara juri, yaitu Azerbaijan, Georgia, Montenegro, Polandia, Rumania, dan San Marino. Skor yang diberikan antarjuri negara tersebut menunjukkan pola yang sangat tidak biasa jika dibandingkan dengan pola voting historis maupun tren umum tahun itu. Akibatnya, EBU membatalkan hasil voting keenam juri nasional tersebut dan menggantinya dengan skor agregat berdasarkan model statistik. Keputusan ini memperlihatkan bahwa praktik politisasi dalam voting tidak hanya berlangsung secara implisit melalui kedekatan budaya atau diaspora, tetapi juga dapat terjadi secara eksplisit melalui koordinasi yang dianggap melanggar integritas kompetisi.
Dengan demikian, analisis terhadap bloc voting, pengaruh diaspora, serta kasus kolusi terkini membuktikan bahwa Eurovision bukanlah ruang yang steril dari politik. Justru sebaliknya, kontes ini menegaskan bagaimana hubungan internasional, migrasi, dan solidaritas regional termanifestasi dalam format budaya populer. Pemahaman atas pola geopolitik ini membuka ruang penelitian lebih lanjut tentang bagaimana hiburan massal dapat mereproduksi maupun menantang konfigurasi kekuasaan di Eropa kontemporer.
Jika pola voting memperlihatkan bagaimana relasi geopolitik dan identitas diaspora termanifestasi dalam hasil akhir, maka dimensi lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana lagu serta simbol visual digunakan sebagai medium komunikasi politik. Alih-alih hanya menjadi karya artistik, sejumlah entri Eurovision justru membawa pesan politis yang lebih halus, baik melalui lirik, pemilihan bahasa, maupun penampilan panggung. Di sinilah terlihat bahwa kontes musik ini berfungsi sebagai arena simbolik, tempat negara-negara menyampaikan isu-isu sensitif tanpa melanggar aturan eksplisit tentang larangan pesan politik.
Salah satu contoh paling menonjol adalah kemenangan Ukraina pada 2016 dengan lagu “1944” yang dibawakan oleh Jamala. Meski secara formal lagu tersebut berkisah tentang deportasi bangsa Tatar Krimea oleh Uni Soviet, banyak pengamat menafsirkan karya ini sebagai metafora atas aneksasi Krimea oleh Rusia pada 2014. Kemenangan “1944” memicu perdebatan sengit mengenai apakah Eurovision masih dapat diklaim sebagai ajang apolitis, mengingat penonton maupun juri memberi dukungan yang dapat dibaca sebagai bentuk solidaritas politik terhadap Ukraina. Kasus ini menjadi bukti bahwa karya seni dapat menyelipkan narasi politik melalui representasi sejarah yang relevan dengan konflik kontemporer.
Penggunaan simbol visual di panggung juga sering dimanfaatkan untuk mengirimkan pesan tertentu. Pada 2007, misalnya, peserta Ukraina Verka Serduchka tampil dengan kostum perak mencolok dan bintang raksasa di kepalanya. Walaupun penampilannya dikemas dalam bentuk parodi dan humor, interpretasi politik tidak terhindarkan, khususnya karena beberapa media Rusia menilai bahwa lagu “Dancing Lasha Tumbai” mengandung sindiran terhadap hubungan Rusia-Ukraina. Perdebatan serupa muncul pada 2019 ketika Madonna tampil sebagai bintang tamu di interval act dan menampilkan penari dengan kostum bendera Palestina dan Israel yang saling bergandengan tangan. Aksi ini, meski bukan bagian dari kompetisi resmi, mempertegas bahwa Eurovision menjadi panggung yang sarat makna politik terselubung, baik dari peserta maupun artis pendukung.
Selain itu, simbolisasi politik juga tampak dalam pemilihan bahasa dan identitas budaya. Banyak negara menggunakan Eurovision untuk menampilkan elemen budaya nasional sebagai bentuk diplomasi budaya. Contohnya adalah penggunaan bahasa nasional minoritas atau instrumen tradisional dalam lagu, yang dapat dibaca sebagai upaya mempertegas kedaulatan identitas. Hal ini bukan sekadar estetika, melainkan pernyataan politik tentang keberadaan suatu bangsa dalam ruang Eropa yang lebih luas. Dengan demikian, Eurovision menjadi ruang performatif di mana politik identitas dinegosiasikan dan dipertontonkan kepada khalayak internasional.
Keseluruhan fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun aturan secara formal melarang pesan politik eksplisit, praktik di lapangan memperlihatkan fleksibilitas interpretasi. Melalui lirik, simbol visual, dan bahasa, para peserta maupun penampil menemukan cara untuk menyalurkan pesan politik secara terselubung. Hal ini semakin menegaskan posisi Eurovision bukan hanya sebagai kompetisi musik, tetapi juga sebagai wadah simbolik di mana politik, identitas, dan seni bertemu dalam format budaya populer transnasional.
Dimensi politik dalam Eurovision tidak hanya muncul melalui simbolisme dalam lagu atau representasi identitas, melainkan juga dalam bagaimana negara tuan rumah memanfaatkan kesempatan menjadi penyelenggara untuk tujuan diplomasi budaya. Hosting Eurovision sering kali dipandang sebagai peluang strategis untuk melakukan nation branding, yakni memperkuat citra internasional, meningkatkan daya tarik pariwisata, dan menampilkan modernitas nasional. Dengan demikian, penyelenggaraan kontes bukan sekadar acara hiburan tahunan, melainkan instrumen soft power yang dapat menghasilkan dampak politik dan ekonomi nyata.
Kasus Azerbaijan pada 2012 menjadi contoh jelas bagaimana Eurovision digunakan untuk memoles reputasi negara. Setelah kemenangan duo Ell & Nikki pada 2011, pemerintah Azerbaijan menggelontorkan investasi besar dalam pembangunan infrastruktur baru, termasuk arena Baku Crystal Hall yang dibangun khusus untuk kontes. Narasi resmi menekankan modernitas, kemajuan ekonomi, dan keterbukaan negara tersebut. Namun, di balik upaya nation branding tersebut, kritik internasional muncul dari berbagai organisasi hak asasi manusia. Amnesty International dan Human Rights Watch menyoroti praktik penggusuran paksa untuk pembangunan venue serta penindasan terhadap kebebasan berekspresi. Kontradiksi ini memperlihatkan bagaimana soft power melalui hosting dapat berfungsi sebagai alat image management yang berusaha menutupi isu-isu domestik yang kontroversial.
Selain aspek politik, penyelenggaraan Eurovision juga memiliki implikasi ekonomi yang terukur, terutama dalam sektor pariwisata. Liverpool sebagai tuan rumah pada 2023—menggantikan Ukraina yang tidak dapat menyelenggarakan akibat perang—melaporkan lonjakan pengunjung yang signifikan. Data resmi menunjukkan bahwa kontes tersebut menghasilkan pemasukan lebih dari £54 juta untuk ekonomi lokal, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor perhotelan, restoran, dan transportasi. Efek serupa juga terlihat di Malmö pada 2024, di mana peningkatan jumlah wisatawan internasional selama periode kontes secara langsung mendongkrak pendapatan kota serta memperkuat posisinya sebagai destinasi budaya. Studi-studi ini menegaskan bahwa di luar dimensi politik, Eurovision berfungsi sebagai katalis ekonomi melalui pariwisata budaya berskala global.
Dengan demikian, hosting Eurovision menegaskan dua fungsi sekaligus: pertama, sebagai instrumen diplomasi budaya yang memungkinkan negara menampilkan citra positif di mata dunia; kedua, sebagai stimulus ekonomi yang nyata bagi kota penyelenggara. Namun, keberhasilan dalam memanfaatkan ajang ini sering kali bergantung pada keseimbangan antara strategi promosi dan respons terhadap kritik internasional. Hal ini menunjukkan bahwa Eurovision bukan hanya kontes musik, tetapi juga arena di mana soft power diuji dan dipertaruhkan melalui praktik nation branding.
Jika hosting Eurovision dimanfaatkan negara untuk memoles citra melalui diplomasi budaya, kasus sebaliknya terlihat ketika partisipasi justru dibatasi atau dicabut. Di titik ini, Eurovision menjadi arena yang tidak hanya berhubungan dengan promosi positif, melainkan juga dengan sanksi budaya terhadap negara-negara yang dianggap melanggar norma internasional. Mekanisme eksklusi ini memperlihatkan bahwa kontes musik tersebut beroperasi dalam ekosistem politik global yang lebih luas, di mana keputusan kultural dapat merefleksikan tekanan geopolitik.
Sejak 2022, Rusia dilarang berpartisipasi dalam Eurovision menyusul invasi ke Ukraina. European Broadcasting Union (EBU) menjelaskan bahwa kehadiran Rusia di kontes akan “mencoreng reputasi” dan bertentangan dengan nilai persatuan yang diklaim sebagai fondasi Eurovision. Keputusan ini menandai pergeseran signifikan, karena sebelumnya kontes sebisa mungkin dipertahankan sebagai ruang inklusif meskipun terdapat ketegangan politik antarnegara. Larangan tersebut dipandang luas sebagai bentuk cultural sanction, yaitu penggunaan instrumen budaya untuk memberikan tekanan politik, melengkapi sanksi ekonomi dan diplomatik yang dijatuhkan Uni Eropa maupun sekutu Barat kepada Rusia.
Kasus serupa terjadi pada Belarus, meskipun dengan konteks berbeda. Pada 2021, EBU mendiskualifikasi entri Belarus karena dianggap memuat pesan yang selaras dengan propaganda pemerintah Lukashenko. Setelah band pengganti yang diajukan juga dinilai tidak sesuai dengan aturan, keanggotaan penyiar nasional Belarus di EBU akhirnya dibekukan. Artinya, Belarus tidak hanya kehilangan akses untuk mengikuti Eurovision, tetapi juga terputus dari jaringan penyiaran publik Eropa. Peristiwa ini menggarisbawahi bagaimana kontes musik dapat dijadikan arena perebutan makna, di mana batas antara hiburan dan propaganda diuji melalui keputusan tata kelola.
Eksklusi Rusia dan Belarus memperlihatkan bahwa Eurovision tidak pernah sepenuhnya netral. Dengan dalih mempertahankan integritas kompetisi, EBU sesungguhnya juga membuat keputusan politik yang berdampak pada legitimasi institusinya. Kritik muncul terkait konsistensi penerapan aturan, terutama karena beberapa negara lain dengan catatan pelanggaran hak asasi manusia tetap diperbolehkan berpartisipasi. Situasi ini memunculkan perdebatan tentang apakah EBU memiliki standar ganda dalam menentukan siapa yang boleh atau tidak boleh ikut serta.
Dengan demikian, Eurovision menjadi cermin dinamika politik internasional: ia dapat berfungsi sebagai panggung promosi identitas nasional, tetapi juga sebagai instrumen eksklusi melalui sanksi budaya. Krisis tata kelola yang muncul dari keputusan-keputusan semacam ini memperlihatkan bahwa kontes musik tersebut tidak hanya menampilkan lagu, melainkan juga memainkan peran penting dalam membentuk norma politik dan hubungan internasional di Eropa kontemporer.
Jika eksklusi Rusia dan Belarus menunjukkan bagaimana Eurovision dapat menjadi instrumen sanksi budaya, maka dimensi lain yang tak kalah signifikan adalah perannya dalam membentuk dan merefleksikan identitas kolektif Eropa. Kontes ini tidak hanya menghadirkan kompetisi musik, tetapi juga memperlihatkan bagaimana “Eropa” didefinisikan, dinegosiasikan, dan ditampilkan di hadapan audiens global. Identitas tersebut senantiasa bergerak antara pluralitas budaya di satu sisi dan garis perpecahan geopolitik di sisi lain.
Momentum dukungan pada Ukraina setelah invasi Rusia pada 2022 memberikan ilustrasi paling jelas mengenai hal ini. Kemenangan Ukraina melalui lagu “Stefania” oleh Kalush Orchestra tidak hanya dilihat sebagai prestasi artistik, tetapi juga sebagai simbol solidaritas politik dari publik Eropa. Hasil televoting menunjukkan lonjakan suara dari hampir seluruh kawasan Eropa, mengindikasikan bahwa masyarakat menggunakan Eurovision untuk mengekspresikan sikap kolektif terhadap krisis internasional. Dengan demikian, kontes ini berfungsi sebagai kanal emosional sekaligus politis, di mana dukungan kultural dialihkan menjadi bentuk solidaritas transnasional.
Lebih jauh, analisis jangka panjang atas pola voting memperlihatkan tumpang tindih antara “Eropa kultural” dan “Eropa politik.” Di satu sisi, dukungan berbasis kedekatan geografis, bahasa, atau diaspora menggambarkan keterikatan budaya yang melintasi batas negara. Namun, di sisi lain, keputusan-keputusan strategis—seperti lonjakan dukungan kepada Ukraina atau pengucilan Rusia—memperlihatkan bagaimana politik praktis ikut membentuk konfigurasi identitas tersebut. Eurovision dengan demikian berfungsi sebagai arena di mana proyek integrasi Eropa dipertarungkan melalui simbol-simbol budaya populer.
Eurovision kini berkembang melampaui sekadar ajang musik tahunan. Ia menjadi ruang bagi Eropa untuk menampilkan identitasnya: penuh keberagaman, namun tak terlepas dari ketegangan politik; merayakan persatuan, sekaligus menghadapi garis perbedaan. Melalui setiap lagu, voting, dan kontroversi, kontes ini terus mengingatkan bahwa identitas Eropa tidak pernah statis, melainkan terus terbentuk dalam interaksi antara budaya dan geopolitik.
Referensi
Charron, N. (2013). Impartiality, friendship-networks and voting behavior: Evidence from voting patterns in the Eurovision Song Contest. Social Networks, 35(3), 484-497.
Dubin, A., Vuletic, D., & Obregón, A. (Eds.). (2022). The Eurovision Song Contest as a cultural phenomenon: From concert halls to the halls of academia (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003188933
European Broadcasting Union. (2009, March 10). Georgian song lyrics do not comply with rules. Eurovision Song Contest. https://eurovision.tv/story/georgian-song-lyrics-do-not-comply-with-rules
European Broadcasting Union. (2021, March 26). EBU statement on Belarusian entry 2021. Eurovision Song Contest. https://eurovision.tv/story/ebu-statement-on-belarusian-entry-2021
European Broadcasting Union. (2022, May 19). EBU statement: Irregular voting 2022. Eurovision Song Contest. https://eurovision.tv/mediacentre/release/ebu-statement-irregular-voting-2022
Eurovision. (2022, May 15). Ukraine’s Kalush Orchestra wins Eurovision Song Contest 2022! Eurovision Song Contest. https://eurovision.tv/story/congratulations-ukraine-kalush-orchestra-win-eurovision-2022
Ginsburgh, V., & Noury, A. (2005). Cultural voting: The Eurovision Song Contest. Public Choice, 134(1–2), 1–12. https://doi.org/10.2139/ssrn.884379
Hesmondhalgh, D. (2000). Western music and its others: Difference, representation and appropriation in music. University of California Press.
Jordan, P. (2014). The modern fairy tale: Nation branding, national identity and the Eurovision Song Contest in Estonia. University of Tartu Press.
Rankin, J. (2021, March 12). Eurovision blocks Belarus entry from pro-Lukashenko band. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2021/mar/12/eurovision-blocks-belarus-entering-pro-lukashenko-song
Raykoff, I., & Tobin, R. D. (Eds.). (2007). A song for Europe: Popular music and politics in the Eurovision Song Contest. Ashgate Publishing.
Spierdijk, L., & Vellekoop, M. (2009). The structure of bias in peer voting systems: Lessons from the Eurovision Song Contest. Empirical Economics, 36(2), 403–425. https://doi.org/10.1007/s00181-008-0202-5




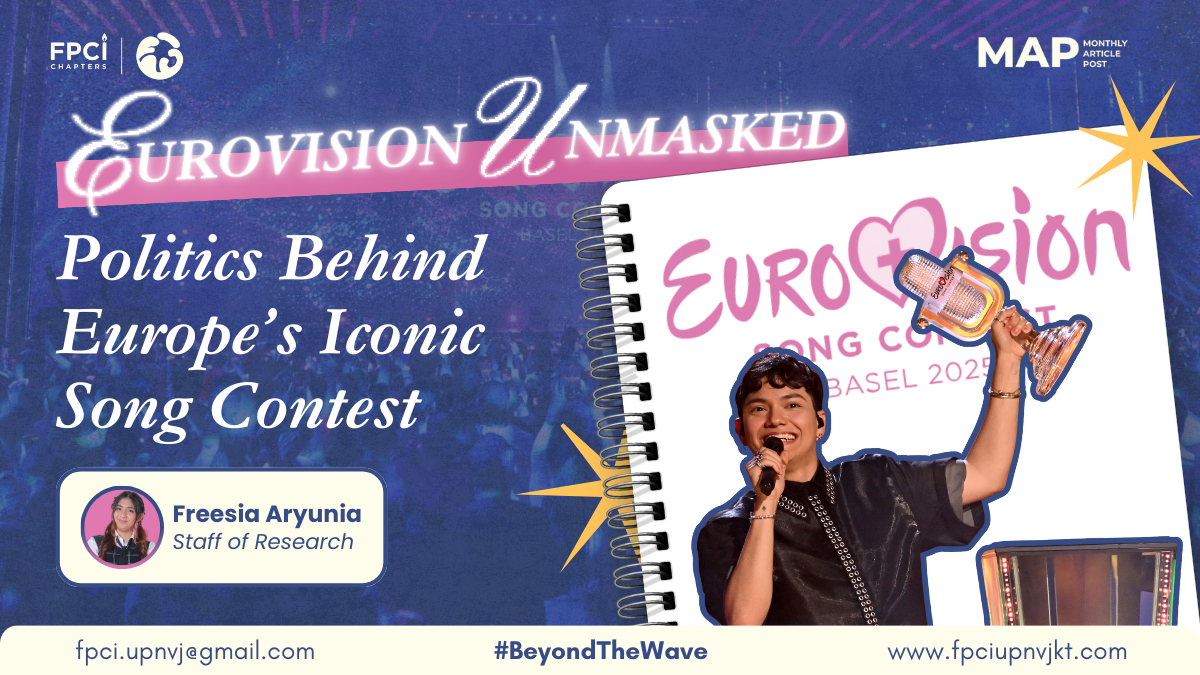

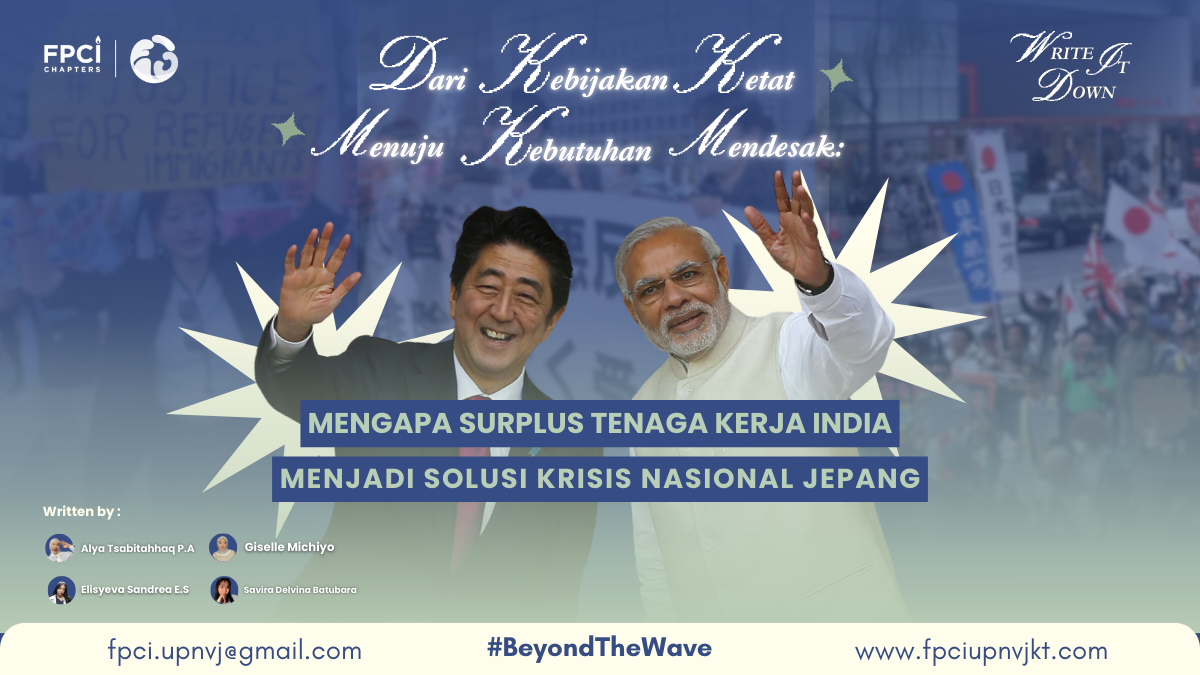

Tinggalkan Balasan