Ditulis oleh Aulia Rasel Widodo & Khilda Fatmawati
Tuvalu merupakan negara kepulauan kecil di Samudra Pasifik yang terletak di antara Australia dan Hawai, dengan populasi sekitar 11.000 jiwa. Negara ini terdiri dari sembilan pulau karang berbentuk melingkar yang menjadi rumah bagi beragam spesies atau yang dikenal sebagai atol dengan total luas daratan hanya sekitar 26 km² yang menjadikannya sebagai negara terkecil keempat di dunia. Ketinggian rata-rata daratannya kurang dari 2 meter di atas permukaan laut, dengan titik tertinggi hanya mencapai 4,6 meter. Letaknya yang datar dan rendah menjadikan Tuvalu sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, terutama kenaikan permukaan laut. Laporan NASA memperkirakan bahwa pada tahun 2050, sebagian besar wilayah Tuvalu, termasuk ibu kota Funafuti akan mengalami banjir pasang harian, dan dalam skenario terburuk 90% wilayah daratannya dapat terendam air laut. Kondisi ini menempatkan Tuvalu sebagai salah satu negara yang paling berisiko kehilangan wilayah kedaulatan secara fisik akibat krisis iklim. Dampak terhadap masyarakat sangatlah signifikah, antara lain yaitu terjadinya migrasi paksa. Lebih dari 4.000 warga Tuvalu atau sekitar 42% dari total populasi telah mengajukan permohonan visa iklim ke Australia sebagai respons terhadap ancaman tenggelamnya negara mereka. Program migrasi ini memungkinkan warga Tuvalu bermigrasi ke Australia setiap tahun melalui perjanjian Falepili Union. Selain itu, jika seluruh wilayah fisik Tuvalu hilang, negara ini berisiko kehilangan status kenegaraan dan warganya terancam menjadi bangsa tanpa tanah air atau stateless nation, dengan tantangan besar dalam mempertahankan identitas, hak hukum, dan akses ke layanan dasar.
Pada November 2023, Australia dan Tuvalu menandatangani perjanjian bilateral yang dikenal sebagai Falepili Union, yakni sebuah bentuk kerja sama yang menandai pendekatan baru dalam diplomasi lingkungan di kawasan Pasifik. Salah satu komponen utama dari perjanjian bilateral tersebut adalah visa iklim. Visa iklim ini memungkinkan 280 warga negara Tuvalu untuk bermigrasi secara permanen ke Australia setiap tahun. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan kedua negara dalam hal keamanan, kemakmuran, dan stabilitas, dengan mengingat adanya ancaman eksistensial yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Melalui visa ini, warga Tuvalu yang terdampak dapat memperoleh akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan di Australia, sekaligus mempertahankan status hukum dan hak-hak sipil mereka.
Hadirnya Australia-Tuvalu Falepili Union Treaty telah menjadi tonggak penting dalam proses pengembangan kebijakan migrasi dan adaptasi iklim yang menyertakan pendekatan hukum, diplomasi lingkungan, serta strategi Australia dalam memanfaatkan soft power untuk mewujudkan kebijakan luar negerinya. Visa iklim yang diusung melalui Falepili Union memungkinkan Australia menyediakan jalur mobilitas khusus kepada warga Tuvalu sebanyak 280 orang setiap tahunnya, baik untuk tinggal di tinggal, bekerja, ataupun menuntut ilmu di Australia secara permanen tanpa diberikan label “pengungsi iklim”. Kebijakan mengenai visa iklim bermula dari penolakan terhadap kerangka konvensional “climate refugee” yang sering kali dikaitkan dengan kehilangan jati diri dan kedaulatan negara asal dengan fokus utama melindungi status hukum serta keberlanjutan eksistensi kenegaraan Tuvalu, meskipun wilayah geografisnya terancam tenggelam akibat kenaikan permukaan laut. Menurut Green dan Guilfoyle (2024), pendekatan ini disebut dengan istilah “legal in-situ adaptation” yang menekankan bahwa meskipun masyarakat Tuvalu bermigrasi ke Australia, mereka tetap memiliki hak atas kedaulatan, identitas nasional, dan yurisdiksi hukum dengan tanah airnya. Hal ini menunjukkan bahwa visa iklim bukanlah sekadar instrumen teknis, melainkan merupakan salah satu bentuk strategi Australia dalam memperkuat pengaruh geopolitiknya di kawasan Pasifik melalui kerja sama bilateral jangka panjang dan diplomasi lingkungan.
Meski demikian, perjanjian ini menuai kritik tajam baik dari kalangan domestik maupun internasional. Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah Pasal 4 Ayat (4) yang mewajibkan Tuvalu melakukan konsultasi dan memperoleh persetujuan dari Australia terlebih dahulu sebelum akhirnya dapat menjalin kerja sama dengan negara atau entitas lain dalam isu pertahanan dan keamanan. Banyak pihak menilai ketentuan ini sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan Tuvalu yang menjadikan visa iklim sebagai “quid pro quo” atau bentuk timbal balik kepada Australia yang telah menawarkan perlindungan migrasi dengan imbalan berupa sebagian pengaruh atas kebijakan luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa, Australia tidak hanya menitikberatkan penggunaan soft power sebagai instrumen dalam berdiplomasi, tetapi juga menyelipkan penggunaan unsur hard power. Pada konteks ini, strategi soft power Australia yang mengusung semangat solidaritas iklim dan kerja sama turut mencerminkan kepentingan nasional yang realistis, khususnya dalam menghadapi persaingan geopolitik dengan negara lain, seperti Cina di kawasan Pasifik Selatan. Diplomasi lingkungan yang diwujudkan melalui Falepili Union turut berperan sebagai instrumen dalam mempertahankan dominasi regional Australia dan memperkuat ketergantungan politik negara-negara kecil di sekitarnya.
Lebih lanjut, kebijakan visa iklim ini turut menimbulkan persoalan etis dan politik yang tergolong rumit. Di satu sisi, kebijakan ini menawarkan solusi nyata dan sah secara hukum bagi ancaman eksistensial yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Akan tetapi, di lain pihak, terdapat pula kekhawatiran bahwa kebijakan visa iklim dapat memicu terjadinya “penghapusan identitas” bangsa Tuvalu. Bagi sebagian warga Tuvalu, skema ini tidak dipandang sebagai langkah penyelamatan yang bermartabat, melainkan sebagai simbol bahwa negara mereka telah menyerah pada tekanan lingkungan dan memilih bergantung pada kekuatan asing untuk melindungi rakyatnya. Pada pemilu 2024, perjanjian ini bahkan menjadi salah satu sorotan utama dan memicu penolakan politik, yang mana seorang tokoh oposisi Enele Sopoaga menyatakan komitmennya untuk membatalkan perjanjian jika terpilih. Kekhawatiran tersebut semakin diperkuat dengan kenyataan bahwa dalam implementasinya, tidak semua warga Tuvalu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh visa tersebut. Selain itu, terdapat pula resiko terjadinya migrasi dalam skala besar yang berpotensi mengganggu kesinambungan struktur sosial dan budaya lokal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Barnett et al (2025), terjadinya perpindahan penduduk hingga mencapai 3,8% dari total populasi Tuvalu setiap tahunnya dapat menimbulkan krisis demografis yang meningkatkan ketergantungan terhadap negara lain serta mempercepat erosi identitas nasional.
Di kancah internasional, Australia turut memperoleh kritik sebab kebijakannya dinilai terlalu condong pada relokasi masyarakat terdampak daripada menangani penyebab utama perubahan iklim itu sendiri. Sebagai negara industri, Australia dikatakan belum melaksanakan tanggung jawabnya secara penuh dalam menurunkan emisi karbon. Australia justru lebih menonjolkan dirinya sebagai “penyokong” bagi negara-negara rentan melalui bantuan teknis dan imigrasi. Hal ini menggambarkan adanya fenomena “repulsion” dalam praktik soft power, yaitu saat suatu negara berusaha menunjukkan citra positif, tetapi justru menimbulkan tanggapan negatif dari pihak lain. Bagi banyak negara kepulauan kecil di wilayah Pasifik, Australia dipandang gagal dalam menunjukkan komitmen moral yang seimbang terhadap prinsip keadilan iklim dan terkesan menjalankan pendekatan yang bersifat selektif serta memanfaatkan negara-negara kecil sebagai alat kepentingan geopolitik. Kebijakan seperti ini turut membuktikan ketimpangan global, yang mana negara besar kerap kali menentukan arah kebijakan, sementara negara kecil hanya menjadi penerima kebijakan yang harus tunduk demi memperoleh perlindungan.
Akan tetapi, meski menuai berbagai kritikan, skema visa iklim yang diatur dalam Falepili Union tetap memiliki relevansi dan berpotensi menjadi contoh bagi negara lain yang menghadapi krisis serupa. Di dunia yang semakin rawan terdampak oleh fenomena iklim ekstrem seperti di Maladewa, Bangladesh, dan Kiribati dapat menjadikan mekanisme visa iklim dapat dijadikan landasan untuk merancang climate humanitarian visa, yakni visa kemanusiaan yang berbasis pada iklim. Mekanisme ini memberikan kesempatan bagi negara-negara penerima untuk menyediakan jalur migrasi yang terorganisir, sah, dan menghormati hak asasi manusia bagi penduduk dari negara-negara yang menghadapi ancaman tenggelam atau kerusakan permanen akibat bencana iklim. Namun, agar skema ini tidak memperparah ketimpangan kekuasaan global, penting untuk menerapkannya dengan mengedepankan prinsip tanggung jawab bersama, tetapi berbeda (common, but differentiated responsibilities), serta menjamin perlindungan atas identitas nasional, kedaulatan, dan hak untuk kembali dari kelompok terdampak. Dalam hal ini, diplomasi lingkungan menjadi sangat penting dalam mendorong terbentuknya kerja sama internasional yang adil, setara, dan berlandaskan solidaritas ekologis.
Secara keseluruhan, visa iklim dalam kerangka Falepili Union memiliki peran krusial dalam mengungkapkan kompleksitas keterkaitan antara migrasi, kedaulatan negara, dan dinamika kekuasaan dalam lanskap politik global saat ini. Di satu sisi, kebijakan ini menunjukkan bahwa diplomasi lingkungan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mendukung strategi adaptasi yang inklusif. Akan tetapi, di sisi lain, kebijakan ini turut memunculkan perdebatan penting mengenai etika hubungan antarnegara dan tanggung jawab global terhadap krisis yang bersifat struktural dan historis. Oleh karena itu, penerapan skema visa iklim perlu disertai dengan perubahan paradigma dalam tatanan hubungan internasional, yang mana upaya adaptasi terhadap perubahan iklim dilakukan bukan untuk memperluas pengaruh suatu negara, melainkan untuk mewujudkan bentuk nyata dari prinsip keadilan iklim global dan tanggung jawab bersama seluruh komunitas internasional. Bagi Australia, Falepili Union menjadi sarana untuk memperkuat perannya sebagai salah satu aktor utama di kawasan Pasifik sekaligus memperluas pengaruh diplomatik melalui pendekatan yang berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas terhadap isu iklim. Namun, adanya penyisipan unsur hard power seperti yang ditetapkan dalam Pasal 4 Ayat (4) menunjukkan bahwa Falepili Union memang mendorong kerja sama secara adaptif, tetapi di sisi lain, perjanjian ini juga menekankan betapa pentingnya keseimbangan solidaritas dengan kepentingan nasional. Sementara itu, bagi Tuvalu, perjanjian ini telah membuka kesempatan nyata bagi warga negaranya untuk bermigrasi secara sah dengan tetap mempertahankan keberlangsungan status kenegaraan melalui legal in-situ adaptation. Akan tetapi, ketentuan yang mewajibkan Tuvalu untuk berkonsultasi dengan Australia dalam isu pertahanan mencerminkan bahwa terdapat pembatasan terhadap ruang kedaulatan. Meski perjanjian ini memberikan solusi atas ancaman eksistensial, perjanjian ini turut berpotensi dalam menciptakan ketergantungan politik terhadap negara mitra.
Referensi
ANTARA News (2025, Juli 2). Air laut naik, hampir separuh warga Tuvalu ajukan pindah ke Australia. ANTARA News. Diakses pada 6 Juli 2025, melalui https://www.antaranews.com/berita/4939609/air-laut-naik-hampir-separuh-warga-tuvalu-ajukan-pindah-ke-australia
Barnett, J., Fatborko, C., Kitara, T., & Aselu, B. (2025). Migration as Adaptation? The Falepili Union Between Australia and Tuvalu. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 16(1), e924.
CNBC Indonesia (2025, Juni 30). Negara Ini Mau Tenggelam, Sepertiga Warga Ajukan Pindah ke Tetangga RI. (2025, June 30). CNBC Indonesia. Diakses pada 7 Juli 2025, melalui https://www.cnbcindonesia.com/news/20250630062736-4-644764/negara-ini-mau-tenggelam-sepertiga-warga-ajukan-pindah-ke-tetangga-ri
Gerlic, Y. (2024). The Australia-Tuvalu’Falepili-Union’Treaty: A Rejection of the’Climate Refugee’in Favor of In-Situ Adaptation. Sustainable Dev. L. & Pol’y, 25, 21., 25(1), 21.
Green, A., & Guilfoyle, D. (2024). The Australia-Tuvalu Falepili Union Treaty: Statehood and security in the face of anthropogenic climate change. American Journal of International Law, 118(4), 684-702.
Liputan 6 (2023, Juni 16). 6 Fakta Menarik Tuvalu, Negara Terkecil ke-4 di Dunia yang Penduduk Aslinya Bangsa Polinesia. Liputan6.com. Diakses pada 6 Juli 2025, melalui https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5319553/6-fakta-menarik-tuvalu-negara-terkecil-ke-4-di-dunia-yang-penduduk-aslinya-bangsa-polinesia
Mares, P. (2011). Fear and Instrumentalism: Australian Policy Responses to Migration from the Global South. The Round Table, 100(415), 407-422.
Martias, D. M. S. (2020). Climate Humanitarian Visa: International Migration Opportunities as Post-Disaster Humanitarian Intervention. Climatic Change, 160(1), 143-156.
McAdam, J. (2025, April 11). New details emerge on new climate migration visa for Tuvalu residents. UNSW SYDNEY. Diakses 6 Juli 2025, melalui https://www.unsw.edu.au/newsroom/news/2025/04/new-details-emerge-on-new-climate-migration-visa-for-tuvalu-residents
Westley, S. (2021). Repulsion as the Antithesis of Attraction in Soft Power Studies: How Australia’s Climate Change Response Has Elicited a Feeling of Repulsion in the Pacific Islands. Linköping University.






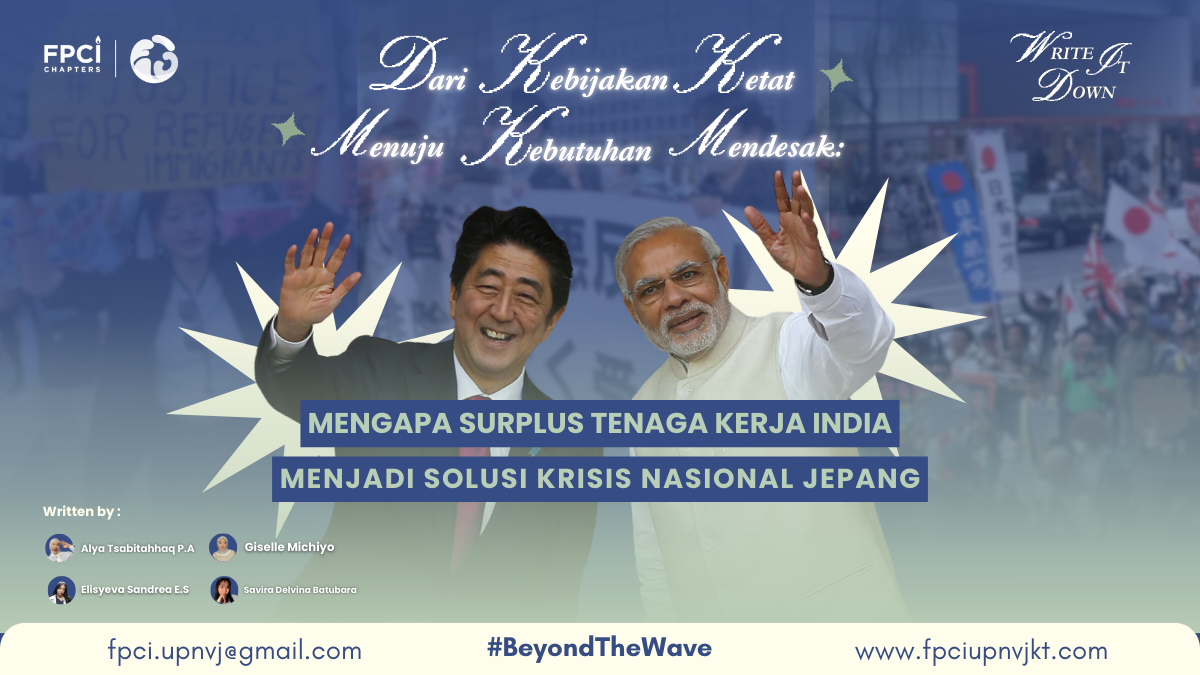

Tinggalkan Balasan